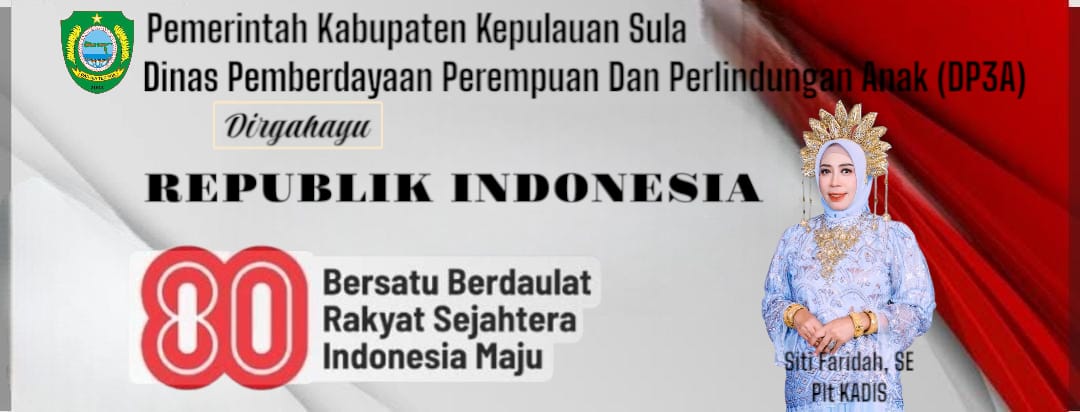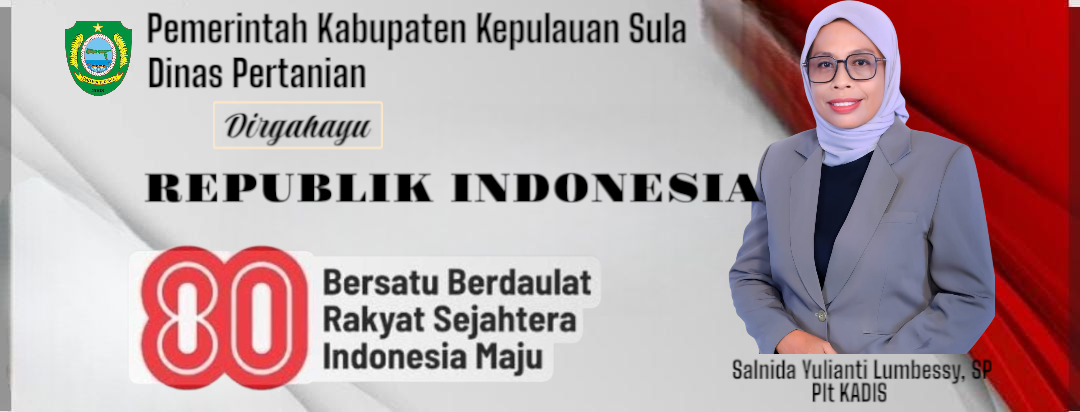Oleh : Moehammad Imron Kadir
Pekerja Humas di Universitas Khairun
DESA punya potensi masing-masing. Ia adalah lembaga yang sudah memiliki kelengkapan sehingga mampu berdiri di atas kakinya sendiri, (Lestary dan Hadi (2021).
Pernyataan itu menegaskan, desa sejatinya lahir dari masyarakat karena diyakini mampu menyelesaikan persoalannya sendiri.
Desa memang ujung tombak pembangunan. Ironisnya, para kepala desa kerap justru menjadi sasaran intimidasi. Antara mengelola dana desa atau menghindari jerat hukum, mereka kini berdiri di persimpangan jalan.
Di Maluku Utara, problem ini terasa nyata. Rata-rata kepala desa masih berhadapan dengan keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Banyak yang hanya bermodalkan ijazah Paket C, tanpa pengalaman teknis memadai untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Kondisi tersebut, membuat pengelolaan dana desa rentan salah langkah. Akibatnya, kepala desa mudah disorot secara tajam oleh oknum lembaga swadaya masyarakat maupun media, yang lebih sering menghadirkan tekanan ketimbang pendampingan.
Padahal, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan otonomi luas bagi desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Desa diharapkan mampu meningkatkan pelayanan publik, mendorong partisipasi warga, hingga menggerakkan ekonomi lokal.
Justeru, kadang-kadang harapan besar itu mustahil terwujud jika kapasitas kepala desa dibiarkan seadanya tanpa penguatan berkelanjutan.
Minimnya pembinaan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) memperparah keadaan. Banyak kepala desa kesulitan menyusun regulasi, mengelola administrasi, hingga menjalankan prinsip transparansi. Celah inilah yang kerap dimanfaatkan pihak luar untuk menekan mereka dengan tuduhan tak berdasar.
Sejak dana desa digelontorkan pada 2015, komitmen pemerintah membangun Indonesia dari pinggiran sudah jelas. APBN 2025, alokasi dana desa mencapai Rp71 triliun. Namun, transparansi dan akuntabilitas masih menjadi pekerjaan rumah. Laporan fiktif, penggelembungan biaya, hingga kasus korupsi dana desa yang sampai ke pengadilan membuktikan persoalan tata kelola belum tuntas.
Selain masalah keuangan, rendahnya kapasitas SDM, juga memperbesar risiko. Banyak perangkat desa masih gagap dalam administrasi maupun manajemen keuangan. Transparansi tanpa literasi justru bisa menjadi jebakan. Kepala desa membutuhkan bekal manajerial, pemahaman hukum, serta keterampilan digital agar tata kelola desa benar-benar akuntabel.
Belum lama, Wakil Bupati Halmahera Selatan, Helmi Umar Muchsin, bahkan mengakui kegagalan pemerintah daerah dalam mengusulkan desa setempat masuk ke Program Strategis Nasional Desa Nelayan.
Justeru, Ia menyebutnya pembelajaran bersama, seraya berjanji memperbaiki kualitas data agar pengusulan 2026 lebih matang. Pengakuan terbuka ini, menggambarkan betapa persoalan kapasitas bukan hanya milik desa, melainkan juga pemerintah daerah.
Ironi terbesar adalah ketika kepala desa lebih sering menghadapi ancaman hukum, pemberitaan tak proporsional, hingga intimidasi, ketimbang ruang belajar. Alih-alih didampingi, mereka bekerja di bawah bayang-bayang tekanan.
Intimidasi jelas bukan jalan keluar. Yang dibutuhkan adalah pendampingan dan penguatan kapasitas berkelanjutan, agar desa tumbuh sebagai pusat pembangunan mandiri. Desa yang kuat akan melahirkan masyarakat sejahtera.
Akhirnya, di atas kertas, desa diberi otonomi luas dan harapan besar. Namun di lapangan, kepala desa masih lebih sering diperlakukan sebagai objek kesalahan daripada subjek pembangunan. Inilah ironi yang menempatkan mereka di persimpangan jalan, maju dengan segala risiko, atau mundur dengan segala stigma.